Kita bisa lega bahwa kita punya nyanyian yang mengatakan
Siapa bilang Bapak dari Blitar ?
Bapak kita dari JawaTimur
Siapabilang rakyat kitalapar
lndonesia kaya dan makmur
Bila orang, menyanyikan sendirian lagu ini, serempak, secara beramai-ramai, orang lain kemudian "nyenggaki"--menyela--dengan bait lanjutannya.
"Marilah kita bergembira, bergembira semua..." dan seterusnya, buat menggambarkan bahwa kita sebagai bangsa tak sedang bersedih. Sebaliknya, kita tampak gembira, optimis, dan hidup semarak. Kita bisa membabat semua jenis halangan yang menghambat jalannya revolusi saat itu.
Kenangan masa kecil mengingatkan, lagu ini populer di kampung saya di musim kemarau panjang. Waktu itu kira-kira sekitar tahun enam tiga, mungkin awal enam
Di musim kemarau panjang itu panen kacang tanah terjadi. Dan di sawah, ketika panenan itu, berita-berita politik beredar di antara orang kampung. Kata seseorang, dan ia cuma mendengar dari orang lain, dan orang lain itu pun mendengar dari orang lain lagi, bahwa kami, orang kampung, memang sengaja dibikin lapar.
Gaplek, bahan pangan utama yang menjadi thiwul itu, kabarnya diangkut dengan kapal laut. Dalam jumlah berton-ton banyaknya, tiap saat, bahan pangan itu ditenggelamkan begitu saja. Katanya, ini sabotase.
Rakyat lapar itu hanya merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya agar negara menjadi lemah. Dan setelah negara lemah, kaum nekolim---neo kolonis---dengan mudah datang kembali menjajah kita.
"Maka, wahai rakyat
Atau cemas. Lebih-lebih karena persoalan tak begitu jelas: musuh kita itu apa, atau siapa? Kaum nekolim itukah, atau perut kita sendiri yang lapar, karena gaplek--sekali lagi katanya--ditenggelamkan ke laut?
Saya kira musuh kita waktu itu dua-duanya: ya kaum nekolim, ya perut lapar. Kaum nekolim itu maksudnya Ingggris dan Amerika. Dan ketika konfrontasi dengan
Abdul Rahman Saleh, PM Malaysia pun tak usah ditakuti. Dia itu cuma boneka Inggris.
Mungkin benar kita saat itu hidup dalam "The Years of Living Dangerously". Pangan buat rakyat sudah susah. Masih harus menghadapi situasi perang. Banyak anak kampung putus sekolah.
Orang bilang, paceklik itu membuat
Tapi meskipun lapar itu urusan perut, dan keberanian--terhadap kaum nekolim--urusan perasaan, di desa pun anehnya ada sedikit kelegaan. Lega, karena kita tak boleh lemah demi menghadapi kaum nekolim tadi. Dan lega, bahwa kita punya nyanyian yang mengatakan
Memang benar, bagi orang kampung saya makna "kaya" dan "makmur" dan lagu itu lebih bersifat ideologis. Mungkin malah berupa mitos. Ia tak bersentuhan dengan realitas, karena bagaimana mau disebut makmur, bila gaplek saja mahal?
Tragisnya, dengan perut lapar kita menyanyi: siapa bilang kita lapar?
Kita melakukan sejenis "self denial" secara beramai-ramai. Kita terbius slogan politik.
***
IRIAN Jaya punya hutan-hutan lebat, dan hutan-hutan itu kaya umbia-umbian. Juga sagu.
Tapi mengapa rakyat di
Hutan yang sudah merupakan sahabat, mengapa tiba-tiba melakukan penghianatan, dan tak memenuhi janjinya memberi makan segenap warga yang hidup di sekitarnya? Apakah mereka sudah bosan dieksploitir terus-menerus? Apakah hutan melakukan protes sendiri secara langsung terhadap orang-orang yang membiarkan terjadinya kebakaran di tempat-tempat lain?
Kita tidak tahu persis apa yang sedang terjadi di
Kelaparan bukan perkara yang dibuat-buat. Keadaan itu bersifat darurat, dan tak bisa menunggu. Bantuan harus segera dikirim. Kalau tidak, kita digugat oleh rasa keadilan kita sendiri.
Tapi mengapa di dalam
Dan mengapa pula, dalam situasi resah begini, ibu-ibu pejabat malah pamer kemewahan liburan ke luar negeri sambil berbelanja dan berobat? Mengapa mereka tak peduli persoalan sensitif tengah melilit hidup kita? Di mana letak Dharma mereka?
Rasa keadilan kita memang dilukai. Tapi segala puji bagi Allah. Kita masih merasa gembira, karena sedikitnya sekarang tak beredar isu bahwa gaplek kita diangkut dan ditenggelamkan ke laut.
Syukurlah kita masih bisa mencoba mengulurkan tangan kepada saudara-saudara kita yang kelaparan di Irian jaya dengan bahan pangan itu. Bila biasanya mereka makan sagu, atau umbi-umbian, kita kirim mereka gaplek agar kini ganti makan thiwul. Semoga program thiwulisasi menyelamatkan mereka.
Tapi omong-omong, perkara "food habit" ini bukan barang mudah diubah. "Food habit" merupakan tradisi yang lama melembaga, berurat dan berakar dalam individu dan masyarakat.
Di luar negeri kita repot belajar makan roti. Dan jangan-jangan, orang-orang yang biasanya makan sagu dan umbi-umbian, tak mudah pula makan thiwul?
Kalau itu benar, bagaimana program thiwulisasi?
Sumber : Tempo 13 Desember 1997










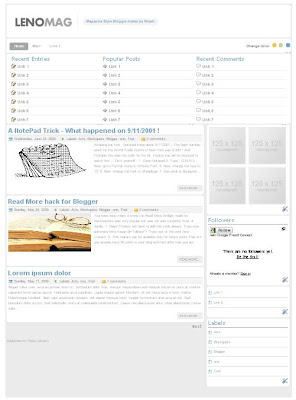

Tidak ada komentar:
Posting Komentar